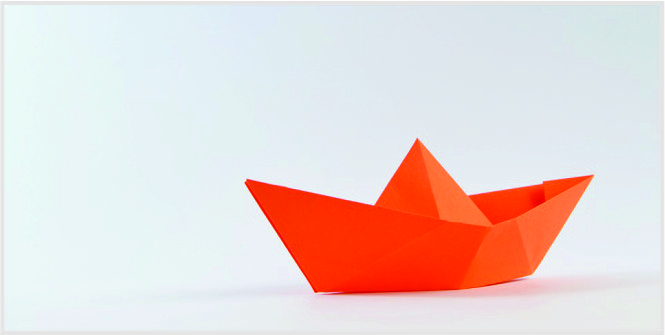Soal:
Wajibkah memilih pemimpin yang buruk di antara yang terburuk, dengan alasan: ahwan as-syarrayn, atau akhaffu ad-dhararayn?
Jawab:
Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal yang harus didudukkan: (1) soal memilih dan mengangkat pemimpin itu sendiri; (2) memilih dan mengangkat pemimpin yang buruk di antara yang terburuk.
Dalam konteks yang pertama, ada beberapa hal yang harus dikemukakan. Pertama: Memilih pemimpin memang wajib, tetapi dalam urusan atau perkara yang dibenarkan oleh syariah. Ketentuan ini berlaku, jika ada sekelompok orang, minimal tiga atau lebih, masing-masing mempunyai urusan yang sama (umûr musytarakah), dan urusan mereka sama-sama dibenarkan oleh syariah. Kesimpulan ini ditarik dari nash hadis yang menyatakan:
«إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ»
Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah).
Frasa fî safar[in] (bepergian) menunjukkan, bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (umûr musytarakah), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (dibenarkan syariah). Dari frasa tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Inilah mafhûm muwâfaqah yang bisa kita tarik dari nash hadis di atas.
Kedua: Kepala negara atau kepala daerah adalah pemimpin yang menjalankan urusan pemerintahan (al-hâkim), yang bertugas menerapkan hukum (munâfidz al-hukm) di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini al-Quran menegaskan:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ
Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian (QS an-Nisa’ [4]: 59).
Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati uli al-amr, yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat (al-hâkim), karena pengertian uli al-amr dalam bahasa Arab tidak ada lain, kecuali al-hâkim. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk semua uli al-amr, melainkan uli al-amr minkum, yaitu uli al-amr dari kalangan umat Islam. Tidak juga untuk uli al-amr yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah, karena kita dilarang untuk menaati orang yang bermaksiat kepada Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Ahmad.1
Karena itu, menaati kepala negara atau kepala daerah Muslim yang menjalankan hukum-hukum Allah adalah wajib; mengangkat mereka pun hukumnya wajib. Sebab, jika mereka tidak ada, kewajiban untuk menaati mereka pun tidak bisa dijalankan. Dengan begitu, hukum memilih atau mengangkat mereka pun menjadi wajib. Ini merupakan bagian dari dalâlah iltizâm ayat di atas.
Namun, para ulama sepakat, bahwa kewajiban dalam konteks ini bukanlah kewajiban orang-perorang (fardhu ‘ain), melainkan kewajiban orang secara kolektif (fardhu kifâyah). Inilah yang dijelaskan dalam hadis baiat.2
Ketiga: Islam mempunyai metode baku untuk mengangkat kepala negara, yaitu baiat. Baiat adalah akad sukarela (‘aqd muradhah) antara rakyat dengan kepala negara untuk memerintah mereka berdasarkan hukum-hukum Allah.3 Karena itu, bisa dikatakan, bahwa baiat adalah satu-satunya metode pengangkatan kepala negara di dalam Islam. Dalam istilah teknis fuqaha’, baiat untuk mengangkat kepala negara tersebut disebut baiat in’iqâd. Sebab, baiat inilah yang secara nyata menandai perpindahan kekuasaan dari tangan umat ke tangan kepala negara (Khalifah). Hukum baiat ini pun wajib. Namun, kewajiban ini tidak bisa dijalankan oleh orang-perorang, karena memang tabiatnya harus dilaksanakan oleh orang secara berkelompok dan mempunyai kemampun untuk menunaikannya.4 Karena itu, disebut fardhu kifayah.
Dengan demikian, hukum baiat in’iqâd dalam rangka mengangkat kepala negara adalah fardhu kifâyah. Karena itu, istilah baiat ini hanya bisa digunakan untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Adapun untuk kepala daerah, pemilihan dan pengangkatannya oleh Islam diserahkan kepada kepala negara.
Ini semuanya terkait dengan mengangkat pemimpin untuk memimpin orang dalam melakukan ketaatan. Adapun mengangkat pemimpin dalam konteks maksiat hukumnya jelas berbeda. Melakukan maksiat hukumnya haram. Karena itu, mengangkat pemimpin dalam konteks maksiat pun sama-sama diharamkan.
Dalam konteks kedua, yaitu memilih dan mengangkat pemimpin yang buruk di antara yang terburuk, penjelasannya adalah sebagai berikut: Pertama, baik-buruk dalam konteks kepemimpinan ini bisa dilihat dari dua aspek: person/orang dan sistem. Boleh jadi secara personal pemimpin yang terpilih tersebut memang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariah, yang berarti, pemimpin tersebut baik. Sebut saja, seluruh syarat yang ditetapkan (syurûth in’iqâd)—seperti laki-laki, Muslim, berakal, balig, adil (tidak fasik), merdeka dan mampu—telah terpenuhi. Namun, dia tidak memerintah dengan menggunakan sistem yang baik, yaitu syariah Islam. Dalam konteks ini, pemimpin yang secara personal baik, namun memerintah tidak dengan menggunakan syariah, maka statusnya adalah salah satu di antara tiga: kafir, fasik dan zalim, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam surah al-Maidah: 44, 45 dan 47. Dengan demikian bisa disimpulkan, mengangkat pemimpin yang tidak memenuhi kriteria jelas tidak sah, sekaligus melanggar ketentuan syariah, dan karenanya tidak baik. Namun, mengangkat pemimpin yang memenuhi kriteria syar’i pun, jika dia diangkat untuk menjalankan sistem sekular juga haram. Karena itu, kedua pilihan tersebut sama-sama tidak boleh, karena sama-sama melanggar hukum syariah.
Kedua, memang ada kaidah syariah:
«إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكاَبِ أَخَفِّهِمَا»
Jika ada dua keburukan, yang harus diperhatikan adalah mana di antara keduanya yang paling besar bahayanya, dengan mengerjakan yang paling ringan di antara keduanya
Ada juga kaidah sejenis yang lainnya. Dalam praktiknya, kaidah ini sering digunakan secara serampangan. Bahkan banyak yang menjadikan fakta (realitas) sebagai penentu yang menentukan pilihan mana yang harus dipilih. Sebagai contoh, ketika kita disuruh memilih, mana yang harus kita pilih: memilih pemimpin yang “baik” dengan sistem sekular atau tidak memilih? Jika kita memilih untuk tidak memilih maka bisa jadi yang akan terpilih adalah pemimpin yang tidak baik, sistemnya pun tidak berubah, alias tetap sekular. Jadi, memilih pemimpin yang “baik” dengan sistem sekular tetap lebih baik ketimbang tidak memilih. Inilah logika akhaffu ad-dhararayn, yang sering mereka gunakan.
Padahal memilih pemimpin untuk menjalankan sistem sekular itu berarti mempertahankan keburukan dan hukumnya jelas haram. Ini bukanlah pilihan satu-satunya yang harus dipilih. Sebab, ada pilihan lain, yaitu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemimpin yang baik, yang menerapkan sistem yang baik, yaitu syariah. Ini hukumnya wajib. Jadi, memilih pemimpin yang “baik” untuk menjalankan sistem sekular tetap tidak wajib, justru haram. Sebaliknya, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemimpin yang baik dengan menjalankan sistem yang baik, yaitu syariah, hukumnya wajib. Wallâhu a’lam. [vm]
Catatan Kaki:
1 Hadits tersebut menyatakan, “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada al-Khaliq (Allah).”
2 Hadits tersebut menyatakan, “Kami membai’at Rasulullah saw. untuk mendengarkan dan mentaati beliau, baik ketika kami susah maupun senang..” Sebagai Nabi dan Rasul, beliau wajib ditaati dan didengarkan perintahnya. Karena itu, sebenarnya beliau tidak perlu dibai’at agar bisa ditaati dan didengarkan perintahnya. Namun, jika ini diperlukan, berarti ada konteks lain, di luar konteks risalah dan nubuwwah, yang mengharuskan beliau juga wajib didengarkan dan ditaati. Itu tak lain adalah konteks pemerintahan. Ini kemudian dipertegas dengan hadits lain, “Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada bai’at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” Konteks tidak adanya bai’at ini adalah tidak adanya kepala negara (Khalifah) yang memerintah berdasarkan hukum-hukum Allah.
3 Lihat, Prof. Dr. Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, Dar an-Nafais, Beirut, Beirut, cet. I, 1426-1996, hal. 95. Dr. Mahmud al-Khalidi, al-Bai’ah fi al-Fikr as-Siyasi al-Islami, Maktabah ar-Risalah al-Islamiyyah, Yordania, cet. I, 1985, hal. 32.
4 Dalam konteks kifayah ini, ulama’ ushul, seperti as-Syathibi memilah pelaku hukum menjadi dua: al-qadir (yang mempunyai kemampuan melaksanakan secara langsung) dan ghair al-qadir (yang tidak mempunyai kemampuan). Al-Farra’ dan Imam an-Nawawi menyebut kelompok al-qadir dalam konteks bai’at in’iqad ini dengan Ahl al-halli wa al-‘aqd, karena memang merekalah yang pemegang simpul-simpul umat. Al-Mawardi menyebut dengan istilah Ahl al-ikhtiyar, yaitu orang-orang yang bisa menentukan pilihan. Lihat, as-Syathibi, al-Muqafaqat, juz , hal. . al-Farra’, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 24. An-Nawawi, Nihayat al-Muhtaj il Syarh al-Minhaj, juz VII, hal. 390. Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 15.