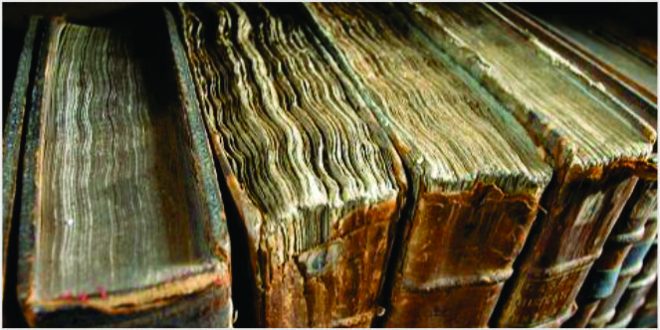Khabar yang diterima (khabar maqbûl) adalah khabar yang lebih dikuatkan kejujuran orang yang menyampaikan berita itu. Ber-hujjah dan beramal dengan khabar maqbûl adalah wajib.
Sebaliknya, khabar mardûd (khabar yang ditolak) adalah khabar yang tidak dikuatkan kejujuran/kebenaran orang yang memberita-kannya. Khabar ini tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak wajib diamalkan (DR. Mahmud Thahan, Taysir Mushthalah al-Hadîts, hlm. 32).
Dalam hal penerimaan atau penolakannya, para ulama hadis dan ulama ushul telah mengklasifikasikan khabar ahad menjadi tiga: sahih, hasan dan dha’if.
Terkait penerimaan ketiga kategori itu, Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah juz I pada bab “Al-Hadîts al-Maqbûl wa al-Hadîts al-Mardûd” menyatakan:
Dari pengklasifikasian hadis menurut para ahli hadis menjadi hadis sahih, hasan dan dha’îf, jelaslah bahwa hadis sahih dan hadis hasan yang bisa dijadikan hujjah, sedangkan hadis dha’îf tidak bisa dijadikan hujjah. Yang menjadikan suatu hadis diterima atau ditolak adalah kajian tentang sanad, perawi dan matan. Jika dari sanad hadis itu tidak hilang seorang perawi—yang hilangnya menyebabkan perawi yang hilang itu tidak bisa ditetapkan adil—dan perawinya tidak dicacat, juga matan-nya tidak lemah (rakîk) dan tidak menyalahi sebagian al-Quran atau as-sunnah mutawatirah atau ijmak yang qath’i, maka hadis tersebut menjadi diterima dan diamalkan serta dijadikan sebagai dalil syariah, baik hadis itu sahih atau hasan.
Adapun jika hadis itu tidak memiliki sifat-sifat tersebut maka hadis itu ditolak dan tidak dijadikan dalil. Atas dasar itu, hadis yang ditolak adalah yang penolakannya bisa disebabkan oleh hilangnya perawi dari sanad yang hilangnya itu mengakibatkan keadilan perawi yang hilang itu tidak bisa ditetapkan, atau disebabkan cacat pada perawi, atau karena kelemahan (rikâkah) hadis atau karena menyalahi apa yang qath’i dari al-Quran, hadis atau ijmak.
Para ulama hadis dan ulama ushul menetapkan hadis yang diterima, sesuai urutannya, ada empat: (1) Hadis shahîh li dzâtihi; (2) Hadis hasan li dzâtihi; (3) Hadis shahîh li ghayrihi (sahih karena dikuatkan oleh yang lainnya); (4) Hadis hasan li ghayrihi (hasan karena dikuatkan oleh yang lainnya).
Sebuah hadis diterima atau ditolak menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul dan ulama hadis. Syarat-syarat secara riwâyat[an], yakni dalam hal sanad dan para perawinya, dan secara dirâyat[an], yakni terkait matan (isi)-nya.
Dalam hal sanad, syarat sebuah hadis diterima sanad-nya harus ittishâl (bersambung) dari awal sanad hingga akhir sanad. Dalam hal perawi maka perawinya harus tsiqah, yakni ‘adil dan dhâbith.
Perawi yang adil adalah jika dia seorang Muslim, baligh dan berakal yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan cacat murû’ah. Keadilan perawi itu ditetapkan dengan keberadaannya yang terkenal (masyhur) dengan kebaikan dan banyak pujian atas dirinya. Jadi siapa yang terkenal keadilannya di antara ahlu an-naqli dan ahlu al-‘ilmi, juga banyak pujian kepada dia sebagai terpercaya dan amanah, maka hal itu cukup menetapkan keadilannya tanpa perlu bukti secara teks (pernyataan). Keadilan perawi juga diketahui dengan penilaian adil oleh para imam atau salah seorang imam.
Adapun perawi yang dhâbith adalah perawi yang dia kuat hapalannya, tidak lupa. Dia hapal dengan riwayatnya jika dia meriwayatkan dengan hapalan, atau dhâbith (akurat) untuk penulisannya jika dia meriwayatkan dari kitab (tulisan). Dia mengetahui makna apa yang dia riwayatkan dan tidak mengalihkan makna dari yang dimaksudkan jika dia meriwayatkan secara makna. Perawi diketahui dhâbith dengan membandingkan dengan riwayat para perawi tsiqah yang dikenal dhâbith (akurat) dan itqân (sempurna). Jika didapati riwayatnya sesuai dari sisi makna dengan riwayat para perawi tsiqah atau sesuai pada galibnya dan menyalahi sedikit sekali (nâdir[an]) maka perawi itu dhâbith (Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah, I/326).
Penilaian keadilan perawi oleh seorang imam diterima baik disebutkan sebabnya atau tidak. Hal itu berbeda dengan penilaian cacat (jarh), tidak bisa diterima kecuali dijelaskan sebabnya. Hal itu karena adanya perbedaan para ulama tentang penilaian sebab seseorang bisa dinilai fasik. Penilaian keadilan dan kacacatan (jarh) itu cukup oleh satu orang imam. Sebab, hal itu pada hakikatnya adalah ikhbâr dan dalam hal itu cukup ucapan satu orang. Jika pada seorang perawi ada penilaian adil berapapun jumlahnya, juga ada penilaian cacat (jarh) disertai penjelasan sebabnya, meski hanya dari satu imam, maka penilaian jarh lebih dikedepankan. Sebabnya, penilaian adil adalah pemberitahuan kondisi perawi secara lahiriah, sedangkan jarh adalah pemberitahuan kondisinya yang tersembunyi dari orang yang menilai adil. Ini berbeda jika imam yang menilai adil mengetahui sebab jarh itu dan menyatakan bahwa perawi tersebut telah tobat darinya dan menjadi baik, maka penilaian adil itu lebih dikedepankan.
Penilaian cacat perawi bisa karena sepuluh faktor. Lima terkait dengan keadilan yaitu: al-kadzib (dusta), tuhmatu al-kadzib (dituduh dusta), zhuhûr al-fisq (tampaknya kefasikan), al-jahâlah (tidak jelas) dan bid’ah. Lima faktor yang lain terkait dengan dhâbthu (keakuratan) yaitu: fahsyu al-ghalath (banyak rancu), fahsyu al-ghaflah (banyak lupa), al-wahmu (bimbang/ragu), mukhâlafah ats-tsiqât (menyalahi para perawi tsiqah) dan sû‘u al-hifzhi (hapalan yang buruk).
Adapun al-majhûl al-hâl (ketidakjelasan kondisi) ada beberapa jenis: Pertama, tidak jelas keadilannya baik zhâhir atau bâthin. Perawi demikian tidak diterima riwayatnya.
Kedua, tidak jelas kondisinya secara bâthin, sementara dia zhâhir-nya adil dan dia al-mastûr. Perawi demikian riwayatnya bisa dijadikan hujjah.
Ketiga, al-majhûl al-‘ayn (tidak jelas orangnya), yaitu setiap orang yang tidak dikenal oleh para ulama dan perawi yang tidak dikenal riwayatnya kecuali dari satu sisi saja.
Ketidakjelasan itu hilang dari seorang perawi dengan ma’rifah (pengetahuan) ulama atas dirinya atau dengan riwayat orang-orang yang adil darinya. Dalam hal itu cukup riwayat satu perawi yang adil sebagaimana dalam penilaian adil cukup dari satu orang imam. Imam al-Bukhari menerima riwayat al-Walid bin Abdurrahman al-Jarudzi, padahal yang meriwayatkan darinya hanya satu orang, yaitu al-Mundzir bin al-Walid. Imam Muslim menerima riwayat Jabir bin Ismail al-Hadhrami, sementara hanya Abdullah bin Wahab yang meriwayatkan darinya (Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah, I/326-327).
Adapun syarat hadis diterima secara dirâyah (matan) adalah jika matan hadis itu tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat baik ayat al-Quran, hadis mutawâtir atau masyhûr. Contohnya, apa yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qays yang berkata, “Suamiku mentalakku dengan talak tiga dan Rasulullah saw. tidak menjadikan untukku tempat tinggal dan tidak pula nafkah.” (HR Muslim).
Hadis ini bertentangan dengan firman Allah SWT:
أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ
Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kalian (QS ath-Thalaq [65]: 6).
Oleh karena itu, hadis tersebut harus ditolak dan tidak boleh diamalkan.
Adapun jika khabar ahad kontradiksi dengan qiyas, maka khabar dikedepankan. Namun demikian, jika ‘illat qiyas itu merupakan ‘illat sharâhah yang dinyatakan oleh nas secara shârih, maka qiyas lebih dikedepankan dari khabar ahad itu (Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah, III/90).
Hanya saja, penilaian suatu hadis sebagai sahih atau hasan itu menurut orang yang berdalil dengannya, jika ia memiliki keahlian untuk mengetahui hadis, bukan menurut seluruh muhaditsin. Hal itu karena ada para perawi yang dinilai tsiqah menurut sebagian muhaditsin bisa dinilai tidak tsiqah menurut sebagian yang lain. Ada juga perawi yang dinilai sebagai perawi majhûl (tidak dikenal) menurut sebagian muhaditsin, tetapi dinilai sebagai perawi ma’rûf (dikenal) menurut sebagian muhaditsin lainnya. Juga ada hadis yang tidak sahih dari satu jalur, tetapi sahih dari jalur lainnya. Ada jalur yang tidak sahih menurut sebagian, tetapi menurut sebagian yang lain sahih. Ada hadis yang tidak dinilai (dianggap) menurut sebagian muhaditsin dan dinilai cacat, tetapi dinilai mu’tabar oleh yang lain dan mereka ber-hujjah dengannya. Ada hadis yang dinilai cacat oleh sebagian ahli hadis, tetapi diterima oleh umumnya para fukaha dan mereka ber-hujjah dengannya.
Sebagaimana tidak boleh tergesa-gesa dalam menerima hadis tanpa mengkaji kesahihannya, demikian juga tidak boleh bersegera menilai cacat suatu hadis dan menolaknya semata-mata karena salah seorang muhaditsin menilai cacat hadis itu dalam hal perawinya. Sebabnya, ada kemungkinan hadis itu maqbûl (diterima) menurut perawi yang lain, dan ada kemungkinan hadis itu dijadikan hujjah oleh para imam dan umumnya para fukaha.
Jadi wajib hati-hati (tidak tergesa-gesa) dan berpikir keras dalam hal hadis sebelum melangkah maju untuk menilai hadis itu cacat atau menolaknya. Siapa yang meneliti para perawi hadis-hadis niscaya ia menemukan banyak perbedaan dalam hal itu di antara para muhaditsin (Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah, bab “I’tibâru al-Hadîts Dalîlan fî al-Ahkâmi asy-Syar’iyyah,” I/346).
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]
 Visi Muslim Media Referensi Islam Kaffah
Visi Muslim Media Referensi Islam Kaffah