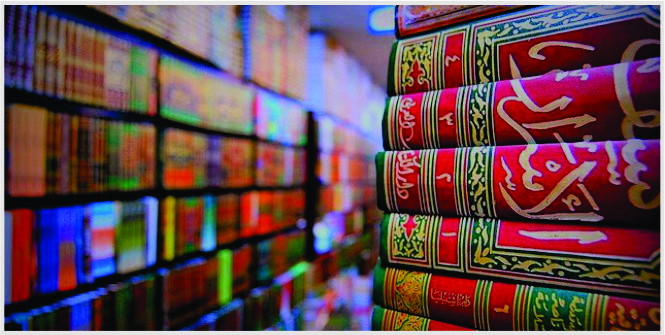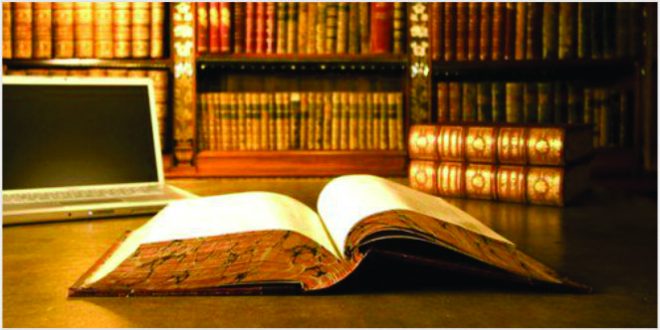Satu dari empat jenis ‘illat syar’iyyah adalah ‘illat dalâlah. Itulah ‘illat yang ditunjukkan oleh nas syara’ secara dalâlah. Artinya, lafal nas atau tarkîb (struktur kalimat) dan tartîb (susunan)-nya menunjukkan pada ‘illat. Penunjukkan ‘illat secara dalâlah ini oleh para ulama ushul disebut juga penunjukkan ‘illat dengan at-tanbîh wa al-imâ` (penginformasian dan pengisyaratan).
Menurut Imam al-Amidi di dalam Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, juga Imam Ibnu Qudamah di dalam Rawdhah an-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh, jenis ‘illat ini ada enam macam. Adapun menurut Syaikh al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani di dalam Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah Juz III, ‘illat ini juga ada enam macam, tetapi beliau mengklasifikasikannya menjadi dua klasifikasi besar.
Klasifikasi pertama: Keberadaan hukum dikaitkan dengan sifat yang memberi konotasi (washf[un] mufhim[un]), yakni memiliki mafhûm muwâfaqah atau mafhûm mukhâlafah. Dalam kondisi ini, sifat tersebut menjadi ‘illat hukum itu. Contoh firman Allah SWT:
۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ …٦٠
Sungguh zakat-zakat itu hanyalah untuk kaum fakir, kaum miskin, para pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya… (QS at-Taubah [9]: 60).
Muallaf itu merupakan pribadi-pribadi Muslim, yang hati mereka dibujuk dengan pemberian zakat. Kata mu’allaf merupakan sifat yang sesuai untuk hukum pemberian zakat itu. Jadi ‘illat mereka diberi zakat adalah membujuk hati mereka agar loyal pada Islam. Kata al-fuqarâ`, al-masâkîn dan al-‘âmilîna ‘alayha juga merupakan sifat. Jadi ‘illat mereka diberi zakat adalah keberadaan mereka sebagai fakir, miskin atau al-‘âmil ‘alayhâ (orang yang diangkat sebagai pengurus zakat).
Contoh lain, ketika nas menyebutkan sifat yang membedakan status hukum dua perkara dengan menyebutkan sifat pada salah satunya. Misalnya, sabda Rasul saw.:
وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا
Pembunuh tidak mewarisi apapun (harta orang yang dibunuh) (HR Abu Dawud dan al-Baihaqi).
Kata al-qâtil adalah sifat yang memberi konotasi sehingga menunjukkan bahwa sifat itu menjadi ‘illat dia tidak mewarisi. Di sini, nas menyebutkan sifat al-qâtil bersama dengan salah satu hukum, yaitu tidak adanya pewarisan dan tidak menyebutkan hukum lainnya, yaitu adanya pewarisan orang yang tidak membunuh. Hadis tersebut memiliki mafhûm mukhâlafah bahwa orang yang tidak membunuh maka mewarisi. Jadi sifat al-qâtil itu disebutkan mengisyaratkan bahwa ‘illat tidak adanya pewarisan itu adalah keberadaannya sebagai al-qâtil (pembunuh).
Contoh lain, sabda Rasul saw.:
مَنْ سَلَّفَ، فَلْيُسَلِّفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
Siapa saja yang melakukan salaf (salam) hendaklah men-salaf pada takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai tempo yang jelas (HR Ahmad dan asy-Syafii).
Al-Kayl dan al-waznu merupakan sifat. Keduanya dikaitkan dengan kebolehan salaf (salam). Ini mengisyaratkan bahwa ‘illat kebolehan salaf (salam) pada sesuatu itu adalah keberadaannya sebagai al-makîl (yang ditakar) atau al-mawzûn (yang ditimbang).
Klasifikasi kedua: Peng-’illat-an itu menjadi kelaziman dari madlûl (makna) kata menurut bahasa, bukan kata itu sendiri. Sebab jika kata itu sendiri yang menunjukkan peng-’illat-an itu maka itu termasuk ‘illat sharâhah. Klasifikasi kedua ini ada lima macam: Pertama, penyusunan hukum berdasarkan sifat menggunakan fâ` at-ta’qîb wa at-tasbîb (huruf fa’ yang menunjukkan akibat atau sebab). Contoh sabda Rasul saw.:
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه
Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, Malik dan asy-Syafii).
Huruf fâ‘ di situ adalah li at-ta’qîb (menunjukkan akibat) sehingga mengharuskan adanya ketetapan hukum, yakni kepemilikan, pasca aktivitas menghidupkan. Hal itu mengharuskan aktivitas menghidupkan tanah mati itu menjadi sebab kepemilikannya. Jadi aktivitas menghidupkan tanah mati menjadi ‘illat kepemilikan atas tanah tersebut.
Kedua, jika terjadi suatu kejadian yang diangkat/diadukan kepada Rasul saw., lalu beliau memutuskan hukum atasnya, maka itu menunjukkan keberadaan apa yang terjadi itu sebagai ‘illat untuk hukum itu. Contoh, Abu Hurairah ra. menuturkan:
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَلِمَ؟ : قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي في رَمَضَانَ، قَالَ: ، فَأَعْتِقْ رَقَبَة، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَين، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّين مِسْكِينًا
Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. Lalu dia berkata, “Celaka aku!” Beliau bertanya, “Mengapa?” Dia berkata: “Aku menggauli istriku pada (siang hari) Ramadhan.” Beliau bersabda, “Klau bagitu, bebaskan seorang budak.” Dia berkata, “Saya tidak punya.” Beliau bersabda, “Berpuasalah dua bulan berturut-turut.” Dia berkata, “Saya tidak mampu.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, berilah makan 60 orang miskin.” (HR al-Bukhari).
Laki-laki itu datang untuk meminta penjelasan hukum syariah atas kejadian yang dia adukan. Lalu Rasul saw. memberitahukan hukumnya sebagai jawaban kepada dia. Beliau bukan menyebutkan hukumnya tanpa ada pertanyaan lebih dahulu. Jadi dalam hal itu diperkirakan (taqdîr) adanya fâ‘u at-ta’qîb, seolah Rasul bersabda: Waqa’ta fa kaffir (Engkau bersetubuh maka tebuslah). Jadi jawaban Rasul saw. itu menginformasikan atau mengisyaratkan bahwa kejadian itu menjadi ‘illat perintah membebaskan budak itu. Dengan demkian persetubuhan pada siang hari Ramadhan menjadi ‘illat tebusan berupa membebaskan budak. Jika tidak bisa maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak bisa maka memberi makan 60 orang miskin.
Ketiga, Asy-Syâri’ menyebutkan sifat bersama suatu hukum yang seandainya tidak diperkirakan sebagai peng-illat-an, niscaya penyebutan sifat itu tidak ada faedahnya, dan itu tidak mungkin. Semua yang disebutkan oleh nas tasyri’ memiliki posisi tasyri’i. Dengan demikian sifat itu dinilai sebagai ‘illat atas hukum itu. Misal, jika berupa jawaban atas pertanyaan, baik sifat itu ada dalam pertanyaan atau dalam jawabannya beralih dari pertanyaan ke padanan pertanyaan itu. Contoh, penyebutan sifat yang ada dalam pertanyaan: Saad bin Abi Waqash menuturkan:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِك
Aku pernah mendengar Rasulullah saw. ditanya tentang jual beli ruthab (kurman basah) dengan kurma. Rasulullah saw. Bertanya, “Apakah ruthab berkurang jika mengering?” Mereka berkata, “Benar.” Beliau lslu melarang hal itu (HR Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Baihaqi, asy-Syafii dan Malik).
Pengaitan larangan atau ketidakbolehan dengan sifat an-nuqshân (susut) dalam jawaban mereka—bahwa ruthab akan susut jika mengering—tidak mungkin sia-sia, artinya pasti punya faedah tasyri’i. Hal itu mengisyaratkan bahwa larangan atau ketidakbolehan jual-beli ruthab dengan kurma itu karena beratnya susut (an-nuqshân).
Contoh pengaitan sifat dengan hukum, yakni sifat itu tidak ada dalam pertanyaan tetapi nas beralih menyebutkan padanannya, Ibnu Abbas ra menuturkan:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى
Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, “Ya Rasulullah, ibuku meninggal dan dia punya utang puasa sebulan. Haruskah aku menunaikan puasa atas namanya?” Beliau bertanya, “Andai ibumu punya utang, apakah engkau membayarnya?” Dia berkata, “Benar.” Beliau bersabda, “Utang kepada Allah lebih berhak ditunaikan” (HR al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan al-Baihaqi).
Dalam riwayat lain yang ditanyakan adalah tentang haji atas orangtua yang sudah meninggal. Jawaban beliau sama seperti di atas. Di situ Rasul saw. tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi menyebutkan utang adami (utang kepada manusia). Dengan kata lain beliau menyebutkan padanan dari apa yang ditanyakan, bukan jawaban atas pertanyaan itu sendiri. Di situ Rasul saw. mengaitkan sifat, yaitu utang, dengan jawaban hukum, dan ini mustahil tanpa faedah. Dengan demikian penyebutan sifat berupa utang dan penyusunan hukumnya menunjukkan adanya peng-’illat-an.
Imam al-Amidi di dalam Al-Ihkâm menyebutkan, yang semisal ini disebut oleh para ulama ushul sebagai at-tanbîh ‘alâ ashli al-qiyâs (penginformasian pokok qiyas). Seolah beliau menginformasikan pokok dan ‘illat hukumnya serta kesahihan pengaitan apa yang ditanyakan melalui ‘illat yang diisyaratkan.
Keempat, di dalam nas disebutkan hukum satu perkara kemudian disusul dengan penyebutan pemisah (tafriqah) dengan perkara lain yang andai tidak disebutkan, niscaya perkara lain itu termasuk dalam hukum perkara itu. Pemisah itu ada lima bentuk (lihat: Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah, III/355-356; Wahbah az-Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, 669-670):
Satu: berupa lafal asy-syarthu wa al-jazâ‘ (syarat dan balasan) dalam bentuk jika … maka…. Contohnya: sabda Nabi saw.:
اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بالْفِضَّةِ، وَالْبرُّ بِالْبِرِّ، وَالشَّعِيْرُ بِاشَّعِيْرِ، وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ، فَبِيعُواكَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَاكَانَ يَدًا بِيَدٍ
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, harus semisal, sama, kontan. Jika berbeda jenis, juallah sesuka kalian jika kontan (HR Muslim).
Pemisah itu memisahkan dua hukum: kebolehan jual-beli sesama jenis jika semisal, sama dan kontan, dengan kebolehan saling berlebih selama kontan jika berbeda jenis. Pemisah itu mengisyaratkan bahwa kesamaan jenis menjadi ‘illat ketidakbolehan jual-beli secara saling berlebih dalam enam jenis itu.
Dua: Pemisah berupa kata tujuan misalnya hattâ (hingga). Contoh firman Allah SWT:
وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ
Janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci (QS al-Baqarah [2]: 222).
Pemisah berupa kata hattâ ini mengisyaratkan bahwa kondisi haidnya istri menjadi ‘illat larangan bersetubuh dengan istri dalam kondisi itu.
Tiga: Pemisah berupa kata pengecualian (al-istitsnâ‘) misal kata illâ. Contoh:
…فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ …
… kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan … (QS al-Baqarah [2]: 237).
Empat: Pemisah berupa koreksi (al-istidrâk) misal kata walâkin (tetapi). Contoh:
لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ
Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah kalian yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kalian disebabkan (sumpah kalian) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hati kalian (QS al-Baqarah [2]: 225).
Lima: Pemisah dalam bentuk melanjutkan salah satu dari dua dengan menyebutkan salah satu sifatnya setelah penyebutan hal lainnya. Contoh:
لِلْفَارِس ثَلَاثَةٌ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ
Untuk penunggang kuda tiga (saham) dan untuk yang berjalan kaki satu saham (HR al-Baihaqi dan ad-Daraquthni).
Lima: Bersama hukum, nas menyebutkan sifat yang memberi konotasi (washf[un] mufhim[un]) bahwa itu untuk menetapkan ‘illat dan memberi konotasi aspek ‘illat. Misal, sabda Rasul saw.:
لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
Janganlah qadhi memutuskan di antara dua orang, sementara dia sedang marah (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan asy-Syafii).
Bersama larangan memutuskan, nas menyebutkan keadaan sedang marah (al-ghadhab). Al-Ghadhab merupakan sifat yang memberi konotasi bahwa itu untuk menyatakan ‘illat dan bahwa al-ghadhab itu merupakan ‘illat untuk larangan memutuskan karena di situ ada kekacauan pikiran dan kondisi. Jadi itu menunjukkan bahwa al-ghadhab merupakan ‘illat larangan memutuskan perkara.
WalLâh a’lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]